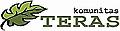Dampak Konversi Hutan di Konawe Utara
Dampak Konversi Hutan di Konawe Utara
Ekspansi Kebun Sawit Percepat Sedimentasi DAS Konaweha
Fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air di hulir sungai Lalindu, kabupaten Konawe Utara, semakin memprihatinkan akibat tingginya sedimentasi karena pengaruh maraknya aktivitas perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan hutan di kecamatan Wiwirano, Langikima, Asera.
AKIBAT pembukaan perkebunan sawit di wilayah itu sejak tahun 1996, kini Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha yang melintasi Konawe Utara pun memburuk dengan total lahan kritis seluas 352.527,67 hektar dari luas 715.067,81 hektar. Sementara tingkat sedimentasi mencapai 295,92 ton pertahun. DAS Konawe menjadi sumber air bagi masyarakat di enam daerah di Sultra yaitu Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan dan Kota Kendari. Hal tersebut dipicu oleh penggundulan hutan dan pembangunan yang tak terencana di daerah hulu, yakni Kolaka dan Konawe Utara.
Saat ini, air sungai Lalindu, bagian tengah DAS Konaweha yang melintasi kabupaten Konawe Utara berwarna coklat, mengalir lamban karena beratnya beban sedimentasi yang dibawa dari bagian hulu. Sungai Lalindu adalah salah satu sub DAS Konaweha yang melewati kecamatan Langkikima, Wiwirano, Asera dan Lasolo. “Ini menggambarkan laju degradasi hutan di wilayah hulu,” kata Amir Mahmud, Kepala Seksi DAS dan Hutan, YascitaKendari.
Menurut Amir, kondisi DAS Konaweha saat ini sedang mengalami permasalahan mendasar dengan adanya penguasaan lahan yang syarat akan masalah, misalnya eksploitasi tambang dan perkebunan besar. Dimana aspek hukum dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan tidak pro kepada masyarakat.
Faisal Misran, staf Seksi Program dan Perencanaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sampara, dalam tulisannya menjelaskan bahwa bagian tengah dan hilir DAS Konaweha juga mengalami tekanan. Tengah dan hilir ditekan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, tambang pasir, pertanian lahan kering tidak konservatif, sedimentasi tinggi, kekeringan sumber mata air, tekanan penduduk yang tinggi, banjir hingga lahan tidur dan irigasi sawah yang terganggu.
Kondisi lahan kritis pada wilayah DAS Konaweha seperti tersebut di atas, membutuhkan prioritas utama dalam pengelolaannya. Selain kritis, pengelolaan DAS Konaweha menjadi prioritas utama karena erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi, terdapat bangunan yang berinvestasi tinggi di bendungan Wawotobi, okupasi lahan yang cukup tinggi yang belum memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah serta merupakan DAS lintas wilayah administrasi kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Kota Kendari.
Hartono, Ekesekutif Daerah WALHI Sultra, mengatakan banyaknya perusahaan yang beroperasi menambah tekanan terhadap lingkungan hidup dan penghancuran keanekaragaman hayati di Kecamatan Asera dan Wiwirano. Ia menyarankan, pemerintah Konawe Utara meninjau kembali dan selektif dalam memberikan izin terhadap perusahaan yang akan masuk di daerah itu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengeluarkan izin. Salah satunya harus memperhatikan AMDAL dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Menurutnya, topografi gunung Asera cekung sehingga arus air cepat merambat turun ke lembah. Disekitar lembah ini terdapat pemukiman penduduk, sehingga pada saat hujan deras mengancam banjir pemukiman penduduk. “Untuk itu, mestinya Pemerintah setempat lebih teliti dalam mengeluarkan izin pembukaan lahan, apalagi kawasan hutan,” katanya.
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Maritim Sultra, Adi Setiadi, menilai gundulnya hutan di Konawe Utara akan berdampak besar terhadap debit air pada DAS Lasolo dan sungai Lalindu. Banjir dan tanah longsor akan mengancam warga disaat musim penghujan. Pengalihan fungsi lahan juga berdampak pada struktur tanah. Saat musim kemarau, tanah menjadi keras dan tandus karena daya serap matahari yang menembus ke tanah.
“Kerusakan DAS otomatis akan menyebabkan tergganggunya kualitas hidup warga yang tergantung pada air tersebut,” katanya. Karena itu diperlukan pendekatan sistem yang terencana untuk menganalisis model hidrologi, pengelolaan tanah dan kebijakan daerah serta pengorganisasian yang melibatkan warga pengguna air agar pengelolaan DAS bisa padu padan dengan satu tujuan menjaminkan ketersediaan air untuk warga Sulawesi Tenggara. Pengelolaan DAS yang memperhitungkan berbagai aspek akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,sosial dan ekologi.
Kelapa sawit adalah jenis tanaman rakus dengan kebutuhan unsur hara dan air. Akar sawit memiliki akar serabut yang sistem perakarannya dangkal, sehingga kurang mampu menahan air dalam tanah dan aliran air permukaan (run off) yang tinggi ketika hujan. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan banjir di hilir, terkikisnya permukaan tanah yang mengandung humus, keruh dan mendangkalnya sungai-sungai, serta dampak negatif lainnya. Ketika musim kemarau lahan mengering, pertanaman sawit itu sendiri kekurangan air, sungai-sungai mendangkal, sungai sebagai prasrana transportasi menjadi terganggu.
(Waode Amrifah)
Perlu Pemetaan Tata Ruang
HUTAN merupakan kawasan yang me miliki fungsi besar bagi kelangsungan hidup manusia. Fakta menunjukkan ketersediaan sumber air sangat tergantung pada kondisi hutan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingginya aktivitas manusia serta binsi pertambangan dan perkebunan, kawasan hutan di Sultra secara cepat hancur dan beralih fungsi.
Di Kecamatan Asera dan Wiwirano, konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu faktor percepatan kerusakan hutan. Kini, puluhan ribu hektar hutan telah gundul untuk budidaya kelapa sawit dan pembukaan tambang. Pembakaran lahan yang kini menjadi bagian dari proses land clearing berkontribusi terhadap naiknya karbondioksida (CO2) yang berdampak pada kesehatan manusia. Tahun 2006, warga Konawe Utara telah menerima dampak pertama dari pengalihan fungsi lahan, yakni banjir bandang.
Investasi yang tak dibarengi dengan sikap transparan dan komitmen terhadap lingkungan adalah salah satu korban dari otonomi daerah. Untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam (PSDA) Pemerintah daerah tak segan-segan mengeluarkan izin atau rekomendasi pada tiap investor yang berkeinginan besar mengelola potensi SDA tersebut, tanpa memperhatikan dampak lingkungan, pengembangan dan penataan kota ke depan.
Konawe Utara yang baru dimekarkan, harus menerima dampak buruk dari aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan yang ijin pengelolaanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, induk Konawe Utara sebelum memekarkan diri. Sebelumnya, Pemkab Konawe sudah menerbitkan izin untuk 40 perusahaan, selebihnya izin diterbitkan oleh Pemkab Konawe Utara sendiri. Prospek yang cerah membuat pemilik modal dari dalam dan luar negeri, dari yang kakap sampai kelas teri, mulai berinvestasi di sektor ini.
Kendati telah banyak perusahaan sawit yang mendapatkan izin, namun tidak satu pun perusahaan yang memberikan hasil dan keuntungan pada masyarakat di Konawe Utara. PT. PN XIV yang telah lama eksis dengan luas lahan yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 4.162 hektar dari rencana seluas 6.000 hektar telah beroperasi kurang lebih 10 tahun. Namun petani sawit baru merasakan hasilnya senilai 250 ribu rupiah. PT. Damai Jaya Lestari yang telah memanfaatkan sekitar 1000 hektar dari rencana pengembangan 16.000 hektar juga belum mengolah buah kelapa sawitnya.
Potret petani sawit di Konawe Utara cukup memprihatinkan. “Tapi ini sudah terlanjur. Kami menerima dampak kebijakan yang buruk dari pemerintah sebelumnya,” kata Abd. Rauf, ketua DPRD Konawe Utara saat audiance di kantor DPRD Konawe Utara dengan tim Joint Campaign YPSHK Green Network, Januari lalu.
Dia menilai, kebijakan yang tepat untuk dilakukan saat ini adalah dengan mempolarisasi kawasan. Menetapkan batas-batas kawasan kelola budidaya dan kawasan proteksi melalui penetapan tata ruang kabupaten. “Sebelum ada aturan tata ruang kabupaten, maka tidak ada izin pembukaan lahan bagi pihak perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan,” katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Konawe Utara, Kahar Haris mengungakapkan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan perkebunan yang memiliki izin pinjam pakai kawasan. Pada umumnya, perusahaan baru mendapatkan izin mencari lokasi dari Pemda Konawe.
“Ini ibarat buah simalakahmah, semua izin terdahulu diterbitkan oleh Pemda Konawe. Tapi semenjak saya menjabat kepala dinas, tak ada izin yang kami berikan. Banyak perusahaan yang mengajukan perpanjangan izin, tapi semuanya saya pending,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah perusahaan perkebunan sawit telah habis masa berlaku izinnya, namun aktivitas masih terus dilakukan. “Kami melihat perusahaan memperalat masyarakat agar mengakui kepemilikan tanah adat, padahal tidak ada dalam kawasan hutan,” tukasnya.
Tak hanya itu, areal perkebunan sawit juga tak jelas batas-batasnya. Pihak perusahaan dengan leluasa menggarap hutan seluasluasnya tanpa batas. Itulah sebabnya, kata Kahar, perlunya tata ruang wilayah agar semua penggunaan kawasan jelas peruntukannya.
Sementara Analisi Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya wajib dimiliki setiap perusahaan sebelum melakukan kegiatan, hingga saat ini tak Perlu Pemetaan Tata Ruang satupun yang memiliki AMDAL. “Sampai saat ini belum ada yang mengajukan AMDAL,” kata Mani Ibrahim, sekretaris Kehutanan Provinsi.
Terkait berbagai fakta di atas, maka pada pada diskusi beberapa waktu lalu yang diselenggarakan di aula dinas kehutanan, dan dihadiri seluruh lembaga peduli lingkungan dan instansi terkait, akhirya sepakat merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau kembali investasi perkebunan sawit di Konawe Utara. Rekomendasi itu diajukan dengan memperhatikan pembukaan perkebunan sawit telah menghasilkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan DAS yang hingga saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
(Waode Amrifah)
Filed under: Media Sultra (Media Lingkungan) | 1 Comment »